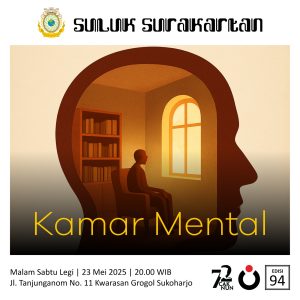Ada masa ketika segala sesuatu yang kita tuangkan kepada dunia terasa tak berpengaruh atau hilang begitu saja. Pengetahuan yang dikumpulkan dengan rentang yang panjang dan susah payah tidak membekas. Nasehat kebijaksanaan pun tidak menemukan ruang untuk tinggal. Gagasan dan perasaan yang kita curahkan justru mengalir ke arah yang tidak kita maksud. Kita lalu bertanya-tanya dalam diam, apakah yang salah pada isinya, atau cara kita menyalurkan dan menerima semuanya?
Setiap manusia memiliki ruang di dalam dirinya, sebagai tempat menyimpan pemahaman dan pengalaman. Tapi ruang ini tak selalu berada dalam posisi siap tampung. Ia bisa miring oleh prasangka, tertutup oleh trauma, atau tumpah oleh kelelahan. Dalam kondisi begitu, sebaik apapun yang dituang, tetap akan meluber atau tidak dapat ditampung. Karena bukan hanya soal apa yang datang dari luar, tapi juga bagaimana bentuk dan kesiapan diri dari dalam.
Di titik inilah kita memahami pentingnya keseimbangan. Keseimbangan bukan berarti selalu stabil, melainkan kemampuan menyesuaikan dan menyadari kondisi diri. Di tengah derasnya informasi, relasi, dan tekanan hidup, ketahanan psikis tak lagi hanya soal “kuat”, tapi tentang tahu batas tampung, menghitung ulang lingkar peran diri, mengatur sudut, jarak dan resolusi pandang. Agar kita tetap bisa menerima dengan jernih. Agar empati tidak berubah jadi beban. Agar batas tidak berubah jadi tembok.
Mbah Nun pernah mengingatkan bahwa manusia bukanlah cangkir yang hanya menadah. “Manusia itu keberadabannya adalah berjalan, bergerak, mencari, bekerja, berdoa, mencoba menemukan. Bukan dikasih tahu, disuguhi, dikasih barang jadi, dan tinggal mengkonsumsi”. Maka menjadi manusia barangkali adalah upaya terus-menerus untuk merawat posisi batin. Agar tidak terlalu miring, tidak terlalu penuh, dan tidak pula tertutup. Karena cara kita menampung hidup, menentukan apa yang bisa tumbuh dan tinggal di dalamnya.
(Redaksi Suluk Surakartan)